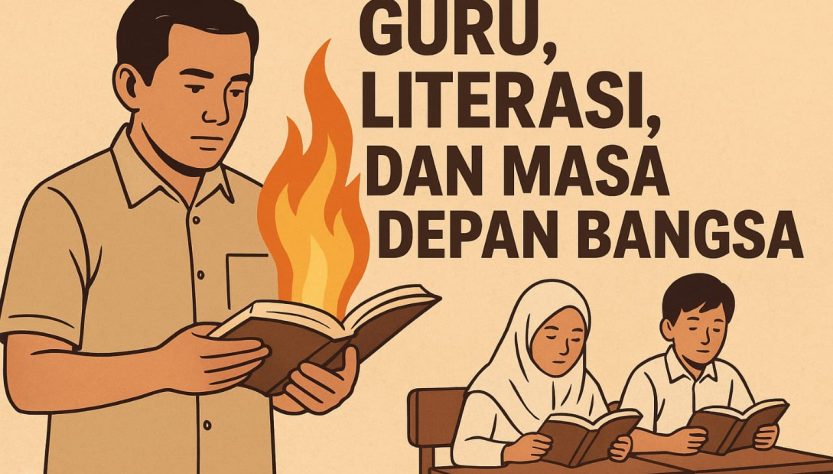Oleh: Denni Meilizon (Penulis, Pegiat Literasi, Ketua Forum TBM Daerah Pasaman Barat, Pembina PGRI Pasaman Barat Bidang Literasi)
Pendahuluan: Fakta dan Realitas
Faktanya, guru-guru kita minim literasi. Pernyataan ini bukan sekadar keluhan emosional, melainkan sebuah diagnosis serius atas kondisi pendidikan kita. Bila membaca menjadi kunci peradaban, maka keterbatasan literasi guru adalah sinyal darurat yang seharusnya membangunkan kita dari tidur panjang. Sebab bagaimana mungkin seorang guru bisa menyalakan api pengetahuan pada muridnya, bila obor yang ia genggam sendiri meredup?
Pertanyaan paling mendasar pun bisa kita ajukan: jika bukan literasi guru yang kita bahas, diskusikan, dan perjuangkan, lalu apa lagi? Persoalan ini bukan sekadar teknis, bukan sekadar soal ujian atau kurikulum yang berubah-ubah. Ini adalah persoalan akar, persoalan fondasi. Bila literasi guru rapuh, seluruh bangunan pendidikan akan mudah retak.
Namun, membicarakan hal ini bukan berarti menuding guru semata. Guru adalah bagian dari sistem. Mereka terjebak dalam pusaran kebijakan, kultur birokratis, dan tekanan administratif. Maka, refleksi ini harus adil: ia menyingkap luka, tetapi juga menawarkan obat; ia menggugat, tetapi juga merangkul.
Potret Buram Literasi Guru: Data dan Fakta
Mari kita tengok cermin yang dipaparkan data.
Hasil PISA 2022 yang dirilis OECD kembali menempatkan Indonesia di papan bawah. Dari 81 negara, Indonesia berada di peringkat ke-71 untuk membaca. Angka ini bukan sekadar tentang murid, melainkan juga mencerminkan kualitas ekosistem pendidikan, termasuk guru sebagai aktor utama.
Survei UNESCO pernah mengungkap bahwa minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001. Artinya, hanya 1 dari 1000 orang yang memiliki minat baca serius. Guru tentu bagian dari masyarakat ini.
Data Kemendikbudristek 2023 menunjukkan bahwa masih banyak guru yang gagap dalam memanfaatkan teknologi literasi digital. Padahal, era digital justru membuka peluang emas untuk memperkaya pengetahuan dan mengakses sumber belajar global.
Riset ACDP (Analytical and Capacity Development Partnership) menggarisbawahi lemahnya budaya membaca di kalangan guru. Banyak guru lebih sibuk menyiapkan administrasi daripada mengembangkan kompetensi literasi dan pedagogisnya.
Apabila data ini disusun dalam mosaik, maka kita menyaksikan wajah buram yang menuntut perbaikan mendesak.
Akar Persoalan: Mengapa Guru Minim Literasi?
Kita tidak bisa hanya menyalahkan individu. Persoalan literasi guru berakar pada sejumlah hal:
– Budaya Birokratis yang Menyandera
Guru lebih sering sibuk mengisi format administrasi, laporan rutin, dan perangkat pembelajaran yang menumpuk. Literasi akhirnya dipersempit menjadi “membaca instruksi” bukan “membaca kehidupan”.
-Lingkungan Sosial yang Tidak Membiasakan Membaca
Buku masih dianggap barang mewah. Perpustakaan sekolah banyak yang sekadar formalitas. Bahkan, di beberapa daerah, buku lebih sulit ditemukan daripada spanduk politik.
-Kurikulum yang Serba Padat
Kurikulum sering berubah, membuat guru terjebak dalam kejar tayang materi. Tidak ada ruang bernapas untuk eksplorasi literasi.
– Minimnya Insentif dan Apresiasi
Guru yang membaca, menulis, dan meneliti jarang dihargai. Sebaliknya, guru yang sekadar mengejar angka kehadiran dan kepatuhan birokrasi justru dianggap “aman”.
– Kesenjangan Digital
Teknologi seharusnya menjadi jembatan, tetapi bagi sebagian guru, ia justru menjadi jurang. Keterbatasan infrastruktur dan kompetensi membuat literasi digital guru tertinggal.
Dampak Krisis Literasi Guru: Gelombang yang Menghantam Generasi
Krisis literasi guru bukan sekadar masalah pribadi. Ia berdampak sistemik:
– Generasi Siswa Minim Inspirasi
Guru yang miskin literasi sulit menghadirkan pembelajaran yang hidup. Siswa hanya dijejali hafalan, bukan diajak berpikir kritis.
-Reproduksi Kebodohan Struktural
Bila guru tidak membaca, ia mengulang metode lama tanpa pembaruan. Murid pun tumbuh dengan wawasan terbatas, melahirkan lingkaran setan kebodohan.
– Rendahnya Daya Saing Bangsa
Di era global, literasi adalah amunisi. Tanpa literasi, kita hanya menjadi penonton, bukan pelaku.
– Tersumbatnya Jalan Inovasi
Guru adalah agen perubahan. Namun tanpa literasi, inovasi hanya menjadi jargon.
Jalan Keluar: Dari Kegelapan Menuju Cahaya
Lalu, apa jalan keluarnya? Refleksi ini bukan sekadar berhenti pada kritik. Mari kita rumuskan solusi:
- Reformasi Sistem Pelatihan Guru
Pelatihan jangan sekadar seremonial. Harus berbasis kebutuhan nyata, terutama literasi baca-tulis dan literasi digital.
- Gerakan Literasi Guru Nasional
Pemerintah bersama ormas, LSM, dan komunitas bisa mendorong gerakan khusus literasi guru. Misalnya, kewajiban membaca satu buku sebulan, disertai forum diskusi reflektif.
- Digitalisasi Perpustakaan
Setiap sekolah perlu didorong membangun perpustakaan digital. Guru bisa mengakses jurnal, e-book, dan bahan ajar global dengan mudah.
- Apresiasi Nyata untuk Guru Literat
Guru yang rajin menulis, meneliti, dan menghasilkan karya harus diberi penghargaan khusus.
- Kolaborasi dengan Komunitas Literasi
Guru tidak boleh berjalan sendiri. Harus ada jejaring dengan taman bacaan, komunitas literasi, dan perguruan tinggi.
Muhammadiyah dan Literasi Guru: Jejak Panjang, Peran Abadi
Dalam konteks solusi, kita tidak bisa menutup mata terhadap peran ormas besar seperti Muhammadiyah.
Sejak awal berdirinya pada 1912, Muhammadiyah telah menjadikan pendidikan sebagai jantung pergerakan.
- Jejak Historis
- Ahmad Dahlan mendirikan sekolah-sekolah modern yang menekankan literasi Al-Qur’an sekaligus ilmu pengetahuan umum. Di masa kolonial, sekolah Muhammadiyah menjadi pusat pembaruan pendidikan dan perlawanan intelektual.
- Ekosistem Pendidikan
Saat ini Muhammadiyah memiliki lebih dari 170 perguruan tinggi, ribuan sekolah, madrasah, hingga TK. Ini adalah ladang subur bagi gerakan literasi guru.
- Gerakan Literasi Kontemporer
Muhammadiyah mendorong lahirnya Pusat Studi, Rumah Baca, dan kegiatan literasi di akar rumput. Guru Muhammadiyah digerakkan untuk menulis, meneliti, dan menghidupkan budaya ilmiah.
- Sinergi dengan Kebijakan Nasional
Muhammadiyah bisa menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun Gerakan Literasi Nasional. Pengalaman panjangnya membuktikan bahwa pendidikan berbasis nilai religius dan rasional bisa berjalan berdampingan.
Di titik ini, Muhammadiyah bukan hanya ormas keagamaan, tetapi juga motor literasi guru. Semangat “Islam berkemajuan” bisa menjadi spirit bagi kebangkitan literasi di Indonesia.
Nahdlatul Ulama (NU) dan Pesantren sebagai Pusat Literasi
Jika Muhammadiyah kuat dalam jalur sekolah modern, Nahdlatul Ulama (NU) menanamkan literasi dalam tradisi pesantren. Literasi di pesantren bukan hanya sekadar membaca buku, tetapi membaca kitab kuning dengan metode bandongan dan sorogan. Tradisi ini menumbuhkan kedalaman berpikir, ketekunan, dan nalar kritis.
Para kiai dan santri terbiasa mengkritisi teks, memberi syarah, bahkan menulis kitab baru sebagai respons terhadap realitas. Dari rahim pesantren lahir tokoh literat seperti KH. Hasyim Asy’ari, KH. Wahid Hasyim, hingga Gus Dur yang dikenal sebagai pemikir sekaligus penulis produktif.
Kini, ketika banyak guru di sekolah umum gagap literasi, pesantren masih menjaga denyut tradisi tulis-baca. Namun tantangannya adalah bagaimana menghubungkan kekayaan literasi pesantren dengan sistem sekolah formal. Guru-guru NU, baik di madrasah maupun sekolah umum, perlu difasilitasi agar tradisi literasi pesantren tidak berhenti di ruang terbatas, tetapi mengalir menjadi arus besar pendidikan nasional.
Komunitas Literasi Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
Selain ormas besar, komunitas literasi independen seperti Taman Bacaan Masyarakat (TBM) juga berperan penting. TBM lahir dari inisiatif warga—sering kali guru atau pegiat literasi—yang menyulap rumah atau ruang sederhana menjadi pusat baca.
Menurut data Perpusnas (2023), terdapat lebih dari 7.000 TBM di Indonesia, meski kondisinya sangat beragam. Di banyak tempat, TBM menjadi ruang guru untuk membaca buku-buku baru yang tidak tersedia di sekolah. Ada pula TBM yang mendorong guru menulis cerita pendek, artikel reflektif, hingga buku antologi.
Komunitas seperti inilah yang sering kali memberi “oksigen” bagi guru yang haus pengetahuan. Tanpa TBM, banyak guru di pelosok tak punya akses bacaan karena perpustakaan sekolah tidak berfungsi. Maka memperkuat TBM sejatinya adalah memperkuat literasi guru juga.
Kolaborasi Ormas, Komunitas, dan Pemerintah
Literasi guru tidak bisa dipikul sendirian, baik oleh pemerintah maupun ormas. Diperlukan kolaborasi tiga pihak:
- Pemerintah menyediakan regulasi, anggaran, dan insentif.
- Ormas seperti Muhammadiyah dan NU menggerakkan jaringan pendidikan mereka.
- Komunitas literasi memberi ruang partisipatif dan pendekatan kultural.
Contoh kolaborasi bisa berupa seperti ini:
Program Residensi Literasi Guru yang dikelola bersama Kemdikbudristek, Muhammadiyah, dan NU, Penerbitan antologi nasional guru Indonesia melalui jaringan TBM dan Festival literasi guru di tingkat daerah yang mempertemukan guru, penulis, ormas, dan pemerintah.
Ajakan Moral dan Filosofis
Bayangkan sebuah kelas. Di sana, seorang guru masuk dengan mata berbinar. Ia membawa buku, kisah, dan pengalaman yang segar. Siswa menyimak bukan karena takut, tetapi karena penasaran. Percakapan di kelas itu tidak lagi sekadar tanya jawab hafalan, tetapi dialog penuh makna.
Kelas seperti ini hanya mungkin lahir bila guru memiliki literasi yang kokoh. Dan literasi guru hanya bisa kokoh bila bangsa ini menaruh perhatian penuh, serius, dan konsisten.
Maka, pertanyaan di awal kembali menggema: Jika bukan literasi guru yang kita bahas, lalu apa lagi?
Bangsa yang besar tidak hanya ditopang oleh jalan tol dan gedung pencakar langit, melainkan juga oleh guru-guru yang mencintai buku, menulis pemikiran, dan menyalakan obor pengetahuan bagi murid-muridnya.
Literasi guru adalah jalan panjang. Mungkin melelahkan, mungkin menuntut pengorbanan. Tetapi tanpa itu, kita hanya berjalan di tempat. Dan bangsa yang berjalan di tempat, sejatinya sedang mundur perlahan menuju kegelapan.
RBP, Ujunggading, 21 September 2025